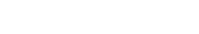Sinopsis
Di akhir abad ke-19, di tengah kepungan kolonial Belanda yang merambah pedalaman Sumatera, muncul seorang tokoh rakyat bernama Datuk Mahara. Dari desa kecil di dataran tinggi Minangkabau, ia memimpin perlawanan yang terlupakan sejarah arus utama. Dengan kecerdikan dan strategi lokal, ia menantang senapan dengan tombak, dan penjajahan dengan harga diri.
Bab 1: Asap di Balik Rimba
Kabut pagi belum sepenuhnya sirna saat Mahara berdiri di puncak Bukit Tambun Tulang. Dari tempat itu, ia bisa melihat seluruh bentang Talang Lubuak, desanya yang dikelilingi rimba lebat dan sawah yang menghijau di musim hujan. Udara masih segar, dingin meresap ke tulang. Di kejauhan, samar-samar tampak gubuk-gubuk beratap ijuk berdiri rapat, seolah saling menghangatkan dalam dingin gunung.
Mahara, putra dari salah satu kepala suku di Talang Lubuak, bukan sekadar pemuda biasa. Di usia duapuluh, ia telah dikenali sebagai penenun kata yang mampu membakar semangat orang-orang, dan sebagai pewaris pusaka yang diturunkan turun-temurun di keluarganya—sebilah keris bermotif ukiran awan dan petir. Tapi pagi ini, wajah Mahara tak tenang.
“Asap,” gumamnya pelan, menunjuk ke arah utara, tempat seberkas abu mengepul dari sela pepohonan. Bukan asap dapur, ia tahu. Terlalu hitam. Terlalu cepat membumbung.
Tak butuh waktu lama untuk memastikan firasatnya benar. Dari jalur berbatu, Leman, seorang pembawa kabar dari suku tetangga, datang tergopoh-gopoh, tubuhnya berlumuran lumpur dan napasnya terengah.
“Mahara! Belanda… Mereka membakar ladang Pak Datuk Caniago! Mereka bilang… itu tanah pemerintah! Warga yang menolak… dipukul… diikat!” teriaknya dengan suara nyaris tercekat.
Mahara mengepalkan tangan. “Sudah kuduga. Mereka mulai dari pinggiran. Uji nyali. Mereka mau tahu apakah kita akan diam.”
“Dan kita?” tanya Leman, matanya tajam menatap Mahara.
Mahara tidak langsung menjawab. Ia menuruni bukit, berjalan cepat menuju balai adat tempat para tetua biasa berkumpul. Di sepanjang jalan, warga mulai keluar rumah. Kabar menyebar seperti api membakar ilalang. Orang-orang bicara berbisik, ada yang marah, ada yang takut. Para ibu memanggil anak-anak mereka, dan para lelaki mulai mengasah parang tanpa diperintah.
Di balai adat, Mahara disambut oleh suara gaduh. Tiga orang tetua telah duduk melingkar: Datuk Bandaro, Datuk Mangkudun, dan tua Ka Sutan. Mereka telah mendengar kabar dan menunggu suara dari Mahara.
“Mereka membakar lumbung kita,” kata Mahara tanpa basa-basi. “Ini bukan lagi soal tanah. Ini peringatan.”
Tua Ka Sutan, lelaki renta dengan sorot mata tajam, mengangguk pelan. “Aku sudah melihat hal ini di masa mudaku. Belanda tidak datang membawa perdamaian. Mereka datang membawa peta dan senjata.”
“Tapi kita belum siap perang,” sela Datuk Mangkudun, raut wajahnya cemas. “Kita hanya punya senjata tajam dan semangat. Mereka punya senapan dan tentara.”
Mahara berjalan ke tengah lingkaran, menatap satu per satu para tetua.
“Kalau kita menunggu siap, maka kita akan siap saat semuanya sudah terlambat. Hari ini ladang Datuk Caniago, besok rumah kita sendiri. Kita harus bersatu sebelum mereka memecah kita.”
Suara Mahara, meski tenang, membawa api. Perlahan, para tetua mengangguk. Mereka tahu, keputusan akan datang, suka atau tidak.
Sore itu, Mahara kembali ke rumahnya di pinggir hutan. Ibunya, Inyiak Saliah, telah menyiapkan air hangat dan nasi singkong. Namun wajahnya suram.
“Anak muda sepertimu harusnya pikirkan menikah, bukan melawan dunia,” katanya lirih.
Mahara tersenyum pahit. “Kalau aku menikah hari ini, besok rumahku bisa dibakar. Apa gunanya membangun kalau tanah tempat kita berpijak dirampas?”
Saliah tak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya, pelan-pelan, seperti tahu pelukan itu mungkin tak bisa diulang.
Malam itu, langit Talang Lubuak gelap dan sunyi. Tapi di dalam hutan, cahaya obor mulai menyala satu per satu. Mahara telah mengundang para pemuda yang bisa dipercaya: Datuk Mudo, Sutan Darek, dan lima belas lainnya. Mereka duduk melingkar, dikelilingi pohon-pohon tua yang seolah menyaksikan pertemuan rahasia itu.
“Kita bentuk jaringan,” kata Mahara pelan, nyaris seperti mantra. “Mulai malam ini, siapa pun yang melihat pergerakan Belanda, beri tanda. Asap, suluh, atau tiupan tanduk kerbau. Kita tak bisa lawan mereka di lapangan terbuka. Tapi kita bisa menjadi bayangan yang tak bisa mereka tangkap.”
“Apa nama gerakan ini?” tanya Sutan Darek, matanya menyala.
Mahara menatap langit yang tertutup kanopi hutan. “Kita sebut diri kita Rimbo Hitam. Seperti hutan ini, kita akan diam, gelap, dan mematikan saat dibutuhkan.”
Orang-orang mengangguk. Dan malam itu, sejarah baru mulai ditulis—bukan di atas kertas, tapi di hati dan darah para pemuda yang telah bosan tunduk pada bayang-bayang penjajahan.
Pagi berikutnya, Mahara kembali ke bukit Tambun Tulang. Matahari mulai menyusup lewat celah-celah daun. Tapi kali ini, ia tak melihat kedamaian.
Di kaki bukit, suara terompet terdengar pelan. Empat serdadu Belanda berkuda melintasi jalan utama desa. Mereka membawa bendera, dan seorang lelaki lokal yang mengenakan baju resmi—penanda sebagai pegawai pemerintah. Warga mulai keluar rumah, ragu-ragu, takut namun penasaran.
Salah satu serdadu turun dari kuda, membuka gulungan kertas besar, dan mulai membacakan pengumuman dalam bahasa Melayu yang kaku:
“Mulai hari ini, seluruh lahan yang tidak disertai surat tanah resmi dari pemerintah Hindia Belanda, dinyatakan sebagai milik negara. Siapa yang menentang, akan dianggap pembangkang hukum kerajaan.”
Mahara berdiri di kejauhan, tangan terkepal. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi ia juga tahu satu hal pasti: tanah ini milik leluhurnya, bukan kertas dan tanda tangan orang asing. Dan selama masih ada napas di dadanya, ia tidak akan menyerah.*
Bab 2: Lumbung yang Terbakar
Udara pagi di Talang Lubuak mengandung aroma yang berbeda. Tak lagi sekadar bau embun dan tanah basah, melainkan jejak bara yang menggantung di angin. Seekor burung alap-alap melintasi langit yang kelabu, seolah menjadi pertanda dari langit akan apa yang akan terjadi.
Mahara sudah terjaga sejak sebelum fajar. Ia duduk di atas bale-bale bambu, menatap api kecil yang membara di perapian. Di pangkuannya tergeletak sebilah keris pusaka, diwariskan oleh ayahnya. Ia mengelus gagang kayu yang halus, memikirkan semua yang telah terjadi—dan apa yang akan segera dimulai.
Ketukan cepat di pintu mengusik lamunannya. Datuk Mudo berdiri di ambang pintu, nafasnya memburu.
“Sudah terjadi,” katanya, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar.
Mahara berdiri. “Di mana?”
“Ladang bawah. Lumbung milik Pak Saman. Dikepung pasukan, lalu dibakar di depan anak-istrinya. Warga yang mencoba melawan dipukul, diikat ke tiang.”
Mahara mengepalkan tangan. Api dalam dadanya menyala. Ia tak butuh perintah. Ini bukan sekadar provokasi. Ini penghinaan.
Ladang Pak Saman adalah salah satu yang terbesar di Talang Lubuak. Lumbung kayunya menyimpan hasil panen dari empat keluarga yang selama musim tanam berbagi tenaga dan tanah. Kini, yang tersisa hanya arang hitam dan puing-puing hangus.
Mahara tiba bersama lima orang dari kelompok Rimbo Hitam. Di tepi ladang, warga berkerumun. Beberapa menangis, yang lain hanya menatap kosong, seperti tak percaya bahwa semuanya telah lenyap hanya dalam semalam.
Pak Saman sendiri duduk di tanah, memeluk lutut, matanya bengkak. “Mereka bilang lumbungku berdiri di atas tanah milik pemerintah. Tapi tanah ini… aku warisi dari ayahku. Dan ayahku dari ayahnya. Mana suratnya? Mana buktinya? Kami tak punya kertas, kami hanya punya ingatan,” gumamnya.
Mahara memandang sekeliling. Asap masih membumbung. Di tanah, ia melihat jejak sepatu berat, lebih lebar dari tapak kaki warga. Tak jauh dari situ, bercak darah—entah darah siapa.
“Warga yang melawan akan dianggap pengacau,” katanya pelan. “Mereka tidak datang untuk memerintah. Mereka datang untuk menghapus.”
Siangnya, Mahara mengumpulkan kembali orang-orang yang tergabung dalam Rimbo Hitam. Mereka berkumpul di gua kecil dekat air terjun, tempat yang hanya dikenal oleh orang dalam desa.
“Apa kita biarkan terus begini?” tanya Sutan Darek, memukul batu dengan marah. “Mereka membakar lumbung, besok rumah kita. Besok mungkin anak-anak kita!”
“Kita harus balas!” seru seorang pemuda lain. “Kita serang pos jaga mereka! Kita bakar markas mereka seperti mereka membakar milik kita!”
Mahara mengangkat tangan, menenangkan.
“Kita bukan penjahat. Kita bukan pembakar. Kita bukan pengecut. Kita adalah penjaga. Tapi siapa yang datang merusak, harus merasakan bahwa kita bukan tanah kosong yang bisa diinjak semaunya.”
Ia membuka lipatan kain dan menunjukkan peta yang ia gambar dari ingatannya—peta letak pos penjagaan Belanda di pinggir desa.
“Ada dua pos kecil. Satu dekat sungai, satu di jalan masuk. Mereka lengah malam hari. Kita tidak akan menyerang seperti bajingan. Kita akan mengambil senjata mereka. Membuat mereka buta. Lalu kita akan tinggalkan tanda. Biarkan mereka tahu: tanah ini bukan milik kertas dan tinta, tapi milik darah dan warisan.”
Orang-orang mengangguk. Malam itu, Rimbo Hitam bersumpah di bawah cahaya bulan.
Saat malam turun, Mahara dan lima pemuda lainnya bergerak menyusuri sungai. Air dingin membelai kaki mereka, dan pepohonan seolah membisikkan doa dalam gelap.
Pos Belanda dekat sungai hanya dijaga dua serdadu. Mereka duduk di bawah lampu minyak, bermain kartu, tertawa dalam bahasa yang asing. Mereka tidak menyadari bahwa dari balik semak, enam pasang mata mengintai.
Mahara memberi isyarat. Dalam hitungan detik, dua pemuda melompat dari belakang, membekap mulut para penjaga dan menjatuhkan mereka ke tanah. Tidak ada darah. Tidak ada suara. Hanya bayangan yang datang dan pergi seperti angin.
Mereka mengambil dua senapan, peluru, dan kantong perbekalan. Di dinding pos, Mahara menggambar simbol Rimbo Hitam—sebuah ranting dan akar melingkar, lambang kekuatan bumi yang tak bisa dicabut.
Keesokan harinya, pos itu ditemukan kosong. Hanya tersisa simbol itu, dan tanah yang diacak-acak.
Kabar itu menyebar. Warga desa yang kemarin ketakutan, kini mulai menyembunyikan hasil panen mereka. Mereka tak lagi menyerah pada ancaman. Mereka mulai menggali lubang untuk menyimpan benih. Sebagian mulai bergabung dalam Rimbo Hitam, menawarkan kayu, makanan, bahkan informasi.
Namun, pihak Belanda tidak tinggal diam.
Tiga hari setelah serangan itu, pasukan tambahan datang dari arah Bukittinggi. Mereka lebih banyak, lebih terlatih. Dan mereka membawa seorang perantara lokal—seorang menantu penghulu yang dikenal dekat dengan penguasa kolonial.
“Ada penghianat di antara kita,” kata Datuk Mudo lirih, setelah melihat perantara itu berbincang akrab dengan pejabat Belanda di pasar. “Ia tahu jalan-jalan hutan. Ia tahu wajah kita.”
Mahara mengangguk. “Kalau ia tahu wajah kita, maka kita harus jadi bayangan.”
Malam itu, Mahara menulis surat. Bukan dengan pena, tapi dengan arang di atas kulit kayu. Ia menuliskan satu kalimat untuk anak-anak cucu yang kelak membaca:
“Kami tidak menulis sejarah dengan tinta, tapi dengan luka dan tanah.”
Lalu ia membakar surat itu, membiarkan abunya terbang tinggi, menyatu dengan langit yang sama yang menyaksikan lumbung pertama dibakar, dan yang akan menyaksikan nyala perlawanan mulai menyala dari balik rimba.*
Bab 3: Sumpah di Puncak Gunung Sago
Langit belum sepenuhnya terang ketika Mahara mendaki lereng Gunung Sago. Embun masih menggantung di pucuk ilalang, dan tanah yang ia injak licin oleh hujan malam sebelumnya. Di belakangnya, Datuk Mudo, Sutan Darek, dan beberapa anggota Rimbo Hitam berjalan dalam diam, membawa perbekalan dan pusaka adat dalam balutan kain beludru tua.
Pagi itu bukan sekadar perjalanan. Hari itu adalah hari penentuan: Mahara telah memanggil para kepala suku dari tiga dataran tinggi—Talang Lubuak, Guguk Ranti, dan Padang Tangah. Di puncak Gunung Sago, tempat yang disakralkan sebagai “atap langit Minangkabau,” mereka akan bersumpah untuk satu hal: melawan penjajahan sampai tetes darah terakhir.
Mahara tahu, ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah tindakan yang berani—bagi sebagian, nekat. Tapi setelah lumbung dibakar dan warga mulai ditangkap satu per satu dengan alasan palsu, tidak ada lagi ruang untuk ragu.
Puncak Gunung Sago diselimuti kabut tebal. Di sana, dalam sebuah dataran kecil berbatu yang disebut Tungku Tigo Sajarangan, para kepala suku telah menunggu. Mereka mengenakan saluak hitam dan kain sarung adat. Di tengah lingkaran, tergeletak sebuah kendi tanah liat dan tiga belati pusaka dari zaman leluhur.
Mahara menunduk hormat. “Assalamu’alaikum, para datuk,” sapanya. Suaranya dalam dan mantap.
“Wa’alaikumussalam,” jawab Datuk Basa dari Guguk Ranti. “Kami datang karena nama ayahmu masih harum di antara kami. Tapi apa yang hendak kau usulkan hari ini, bisa mengakhiri banyak hidup.”
Mahara berdiri di tengah lingkaran. Ia menarik napas, lalu berbicara.
“Para datuk, kita telah mengalah terlalu lama. Mereka datang bukan untuk bertukar kebaikan, tapi menancapkan panji kekuasaan. Mereka bakar lumbung kita, rampas tanah kita, dan ancam adat yang kita warisi dari zaman nenek moyang. Jika kita terus membungkuk, anak cucu kita tak akan kenal arti berdiri.”
Beberapa kepala mengangguk pelan. Yang lain masih diam.
Datuk Malin dari Padang Tangah berbicara, “Tapi melawan Belanda artinya menantang petaka. Senapan mereka bisa menembus kayu ulin. Satu desa bisa dihancurkan hanya karena seorang pemuda berani.”
Mahara mengangguk. “Karena itulah kita harus bersatu. Tidak ada satu suku pun yang cukup kuat sendirian. Tapi jika kita bergerak sebagai satu tubuh, mereka tidak bisa menumbangkan kita satu per satu.”
Ia membuka ikatan di sabuknya dan mengeluarkan potongan kulit kayu bertuliskan simbol Rimbo Hitam.
“Ini bukan sekadar lambang. Ini adalah peringatan bahwa kita bukan pohon tunggal. Kita adalah rimba. Bila satu ditebang, yang lain akan tumbuh menggantikan.”
Suasana hening sejenak. Lalu Datuk Basa berdiri. Ia menatap langit kabut yang memutih.
“Di atas tanah ini, aku kehilangan cucuku karena demam. Tapi lebih perih melihat tanah ini kehilangan martabatnya. Aku setuju, Mahara. Kita bersumpah hari ini.”
Satu per satu, para datuk lainnya berdiri. Dan ketika matahari akhirnya menembus kabut, mereka membentuk lingkaran mengelilingi kendi tanah liat.
Sumpah itu diucapkan dengan bahasa tua, bahasa pusaka yang hanya digunakan pada upacara adat dan peperangan besar:
“Demi tanah yang kami pijak, dan darah yang kami warisi, kami bersumpah untuk menjaga kehormatan anak negeri. Siapa yang mengkhianati sumpah ini, biarlah tanah menolak jenazahnya dan langit menutup jalannya ke atas.”
Setelah sumpah, setiap kepala suku memercikkan darah dari jari ke dalam kendi. Darah itu melambangkan kesatuan tekad. Lalu kendi ditutup dan dikuburkan di bawah batu besar, tanda bahwa sumpah itu bukan sekadar janji lisan, tapi ikatan batin yang akan hidup bahkan setelah mereka tiada.
Setelah pertemuan di Gunung Sago, rencana perlawanan dibentuk secara terorganisir. Mahara ditunjuk sebagai pemimpin Rimbo Hitam, bukan hanya karena keturunan, tapi karena keberanian dan kepiawaiannya dalam menyusun taktik.
Mereka membagi peran:
Guguk Ranti menjadi titik logistik—menyimpan beras, garam, dan senjata hasil rampasan.
Padang Tangah mengatur mata-mata dan pengumpul informasi di kota.
Talang Lubuak menjadi pusat pelatihan dan rekrutmen pemuda.
Gerakan perlawanan mulai terstruktur. Para pemuda dilatih mengintai, membuat jebakan, membaca jejak di hutan. Beberapa tua-tua desa mengajarkan ilmu bela diri silat harimau dan ilmu jalan hening.
Mahara juga mengirim utusan ke beberapa nagari lain, membawa kabar tentang persatuan baru ini. Dalam surat-surat rahasia yang disimpan dalam bambu kecil, ia menulis:
“Jika hari ini kita diam, maka besok anak-anak kita tak tahu cara bersuara. Mari bersatu, bukan karena benci, tapi karena cinta kepada tanah dan langit kita.”
Namun di balik kekuatan yang tumbuh, bahaya pun membayang. Pengkhianatan mulai menyusup perlahan. Seorang pemuda bernama Rasuan, yang dulu anggota Rimbo Hitam, mulai jarang muncul. Ia dikenal licin dan tamak. Beberapa mengatakan ia terlihat berbincang dengan pembesar Belanda di pasar Koto Baru.
Sutan Darek membawa kabar itu pada Mahara. “Kita tak bisa biarkan ular bersarang di dalam rimba.”
Mahara mengangguk. Tapi ia tahu, menghadapi pengkhianat lebih sulit daripada melawan musuh yang terang. Ular berbisa tak datang menggertak, tapi menunggu saat untuk menyusup dan menyengat.
“Biarkan dia percaya kita tak tahu,” kata Mahara akhirnya. “Kita ikuti jejaknya. Tapi jangan bertindak sampai kita yakin. Jangan biarkan amarah mengaburkan akal.”
Menjelang akhir bulan, Mahara memanggil seluruh Rimbo Hitam berkumpul kembali di Hutan Lubuak Silau. Di sana ia berdiri di atas batu besar, menghadap lebih dari seratus pemuda yang kini menjadi bagian dari barisan perlawanan.
“Waktu kita tak panjang,” katanya. “Belanda akan mencium pergerakan ini. Tapi ingat, kita bukan pasukan. Kita adalah bayangan. Kita adalah bisik yang mereka tak bisa bunuh.”
“Mulai malam ini, kita hidup dalam senyap. Tidak semua kita akan membawa senjata. Tapi semua kita adalah senjata.”
Malam itu, obor dinyalakan satu per satu. Simbol api kecil yang menyala di tengah gelap—pertanda bahwa walau kecil, cahaya itu akan menyebar. Dan ketika rimba telah menyala, tak ada penjajah yang bisa berjalan tanpa terbakar.*
Bab 4: Darah di Sungai Batang Agam
Kabut masih menggantung rendah di sepanjang bantaran Sungai Batang Agam ketika Mahara duduk berjongkok di balik semak belukar. Ia mengamati arus air yang tenang, yang sebentar lagi akan menjadi saksi pertempuran pertama Rimbo Hitam melawan pasukan Belanda.
Di seberangnya, dalam bayang-bayang pepohonan, barisan serdadu kolonial terlihat mulai bersiap. Mereka datang dalam kelompok kecil, hanya dua puluh orang, tapi persenjataan mereka lengkap: senapan, belati, dan dua kuda pengangkut logistik. Mahara tahu, mereka hendak menyeberang dan mengambil jalur sempit menuju Bukit Tinggi untuk memperkuat markas.
Tapi hari itu, jalan itu akan tertutup. Rimbo Hitam telah menyiapkan segalanya.
Tiga hari sebelumnya, Sutan Darek membawa kabar bahwa pasukan Belanda akan melewati jalur sungai. Rencana itu bocor dari surat rahasia yang secara tak sengaja ditemukan oleh seorang anak pengumpul kayu di pinggiran Koto Baru. Mahara segera mengumpulkan orang-orangnya.
“Kita tak bisa membiarkan mereka lewat begitu saja,” katanya. “Mereka membawa suplai senjata dan obat. Jika mereka berhasil, maka kita akan menghadapi pasukan yang lebih kuat lagi di hulu. Ini kesempatan pertama kita menunjukkan bahwa tanah ini tidak bisa dilewati tanpa izin.”
Rencana disusun cepat: jebakan dibuat di tanah berawa, pohon-pohon ditebang diam-diam untuk menutup jalur mundur, dan pemanah diletakkan di atas tebing sungai. Rimbo Hitam tak berniat membunuh tanpa sebab—mereka ingin menunjukkan perlawanan, bukan sekadar pembalasan.
Pagi itu, Mahara memberi isyarat dengan gerakan tangan. Sepuluh pemuda bersenjata tombak dan parang bergerak ke sisi kiri. Sutan Darek bersama empat pemanah naik ke punggung bukit. Mahara sendiri tetap di semak, mengawasi dan menunggu.
Langkah-langkah berat mulai terdengar. Pasukan Belanda berjalan dalam barisan. Di depan, letnan berambut pirang membawa peta, berbicara dalam bahasa yang asing tapi penuh perintah. Dua serdadu lain mulai menurunkan perahu dari punggung kuda.
Saat dua orang melangkah ke air, Mahara mengangkat tangan tinggi. Sebuah anak panah melesat dari atas bukit—menancap di tanah, hanya dua jengkal dari kaki mereka.
Letnan berteriak panik, “Siapa di sana?!”
Tak ada jawaban.
Lalu panah kedua melesat—menembus bahu seorang serdadu. Ia jatuh, meraung kesakitan. Seruan panik membahana. Para serdadu mengangkat senjata, menembak ke arah bukit. Tapi tak satu pun mengenai sasaran. Rimbo Hitam telah menyebar dan menyatu dengan rimba.
Pertempuran pecah dalam hitungan detik. Mahara dan para pemuda menyerbu dari kiri, menyerang sisi yang paling lemah. Beberapa serdadu Belanda yang terkejut tak sempat menembak—mereka dipukul jatuh dan dilucuti senjatanya.
Namun, tak semua berjalan mulus. Letnan berhasil menarik pelatuk dan menembak seorang pemuda bernama Yamin di dada. Darah membuncah, dan Mahara, yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, hampir kehilangan kendali.
“Yamin!” teriaknya, berlari ke arah tubuh sahabatnya yang tersungkur.
Tapi dari semak belakang, letnan itu kembali mengokang senjata. Tanpa pikir panjang, Mahara melempar tombaknya—lurus ke arah dada si letnan. Senjata itu menancap dalam, menjatuhkan pria asing itu seketika.
Pertempuran berlangsung tak lebih dari dua puluh menit. Sepuluh serdadu Belanda tewas, sisanya melarikan diri ke hutan, meninggalkan peralatan dan dua kuda yang ketakutan.
Tubuh Yamin dibaringkan di bawah pohon jati. Mahara berlutut di sampingnya, mengelus rambut anak muda itu yang masih hangat.
“Dia mati bukan sia-sia,” bisik Mahara. “Dia mati agar yang lain tahu bahwa kita bukan budak. Kita punya tanah. Kita punya harga diri.”
Kabar kemenangan di Batang Agam menyebar cepat. Di pasar-pasar, orang-orang berbicara dalam bisik-bisik: “Pasukan putih dikalahkan di sungai. Pemuda-pemuda hutan lebih pintar dari tentara.”
Semangat meledak. Anak-anak muda mulai berdatangan dari nagari-nagari lain: dari Taram, dari Kapalo Koto, dari Balai Panjang. Mereka ingin bergabung, ingin belajar, ingin melawan.
Namun Mahara tahu, kemenangan ini juga membawa risiko baru. Belanda pasti tak akan tinggal diam. Balas dendam akan datang, dan mungkin lebih kejam dari sebelumnya.
Benar saja.
Tiga hari setelah pertempuran, utusan rahasia datang membawa berita dari Koto Baru: Belanda mengirim pasukan besar dari Payakumbuh. Mereka membawa meriam ringan dan pasukan berkuda.
Dan yang paling menyakitkan: mereka membawa daftar nama. Nama-nama orang yang dicurigai sebagai bagian dari Rimbo Hitam.
Mahara memandangi daftar yang ditulis di atas kertas Eropa. Beberapa nama sudah dikenalnya: dirinya, Sutan Darek, Datuk Mudo. Tapi satu nama membuatnya terdiam cukup lama.
Rasuan.
“Dia ada dalam daftar?” tanya Mahara.
“Tidak sebagai anggota,” jawab si utusan. “Tapi sebagai pemberi informasi.”
Mahara menatap langit. Wajah Yamin yang gugur masih membayang. Kini ia tahu: kematian itu bukan hanya akibat peluru asing, tapi juga karena lidah beracun milik saudara sendiri.
Di malam yang sama, Mahara berkumpul dengan para kepala Rimbo Hitam di Hutan Baringin.
“Kita menang hari ini, tapi musuh kita tahu lebih banyak dari yang seharusnya,” katanya. “Kita sedang diawasi. Disusupi. Dan itu lebih berbahaya dari ribuan tentara.”
Datuk Mudo menunduk. “Apa kita tangkap saja si Rasuan?”
Mahara menggeleng. “Bukan sekarang. Jika kita gegabah, dia akan lari dan membawa lebih banyak rahasia. Biarkan ia merasa aman. Kita kendalikan langkahnya.”
Sutan Darek menatap Mahara. “Dan selanjutnya?”
Mahara berdiri. Ia melihat jauh ke arah lembah, tempat Sungai Batang Agam mengalir tenang, seolah tak pernah melihat darah mengalir di permukaannya.
“Selanjutnya, kita pastikan darah yang tumpah tidak sia-sia. Kita pastikan nyawa yang pergi membentuk jalan baru bagi yang masih hidup. Kita lawan. Dengan akal. Dengan rimba. Dengan sumpah yang kita kubur di Gunung Sago.”
Ia menatap sekeliling. Wajah-wajah muda, penuh luka tapi juga penuh semangat. Mereka bukan tentara. Mereka bukan pemberontak. Mereka adalah anak tanah yang tak rela kehilangan warisan.
Dan perang baru saja dimulai.*
Bab 5: Muslihat di Balik Bambu
Hujan turun rintik-rintik ketika Mahara menjejakkan kaki di tepian hutan bambu di Nagari Koto Nan Tuo. Di tempat itulah ia dan para pemimpin Rimbo Hitam menyusun strategi paling berani mereka sejauh ini—sebuah operasi senyap untuk mengguncang logistik Belanda di jantung Payakumbuh.
Mahara berdiri di bawah rimbunan bambu tua. Angin meniup ujung-ujungnya, menciptakan suara berderak lembut, seakan alam sendiri tengah berbisik. Di sinilah rencana yang disebut “Muslihat di Balik Bambu” dimulai—bukan dengan senjata, tapi dengan akal dan ilusi.
Beberapa hari setelah pertempuran di Batang Agam, Mahara memanggil Sutan Darek dan Datuk Mudo ke sebuah pondok tersembunyi di dalam hutan.
“Belanda akan membalas, itu pasti. Tapi mereka akan menduga kita akan bertahan. Maka kita serang—bukan dari depan, tapi dari dalam.”
Mahara meletakkan peta kasar di atas meja kayu: Payakumbuh, dengan markas pasukan kolonial di tengah kota, gudang logistik di sisi barat, dan pasar yang menjadi pusat interaksi masyarakat.
“Kita tak bisa menyerbu langsung,” kata Mahara, “tapi kita bisa membuat mereka saling curiga. Kita buat mereka tak percaya pada mata-mata mereka sendiri. Kita buat mereka melihat musuh di setiap bayangan.”
Datuk Mudo mengerutkan kening. “Dengan apa?”
Mahara tersenyum. “Dengan bambu. Dan bisikan.”
Malam itu, lima orang pilihan menyelinap ke Payakumbuh. Mereka menyamar sebagai pedagang arang, penjual pisau, bahkan penggali parit. Mereka membawa kantong kecil berisi surat palsu, peta buatan, dan—yang paling penting—potongan bambu kecil yang diukir lambang Rimbo Hitam.
Setiap malam, mereka tinggalkan benda-benda itu di sudut-sudut tertentu: dekat gudang senjata, di balik pintu penginapan Belanda, bahkan di kamar seorang serdadu yang dikenal haus judi. Tujuannya satu—menyebar rasa takut, bahwa perlawanan sudah menyusup ke jantung kota.
Pada hari keempat, seorang letnan Belanda dilaporkan menembak pelayannya sendiri karena mengira ia mata-mata. Dua serdadu lain ditangkap karena kedapatan membawa bambu berukir. Sementara itu, penduduk lokal mulai berbisik bahwa hantu hutan dari Rimbo Hitam sudah menari di jalan-jalan Payakumbuh.
Tak cukup hanya dengan ketakutan, Mahara merancang aksi besar: pembakaran gudang logistik.
Rencana itu hanya melibatkan tujuh orang. Mereka menyelinap pada malam gelap, saat langit tertutup awan dan angin berhembus dari arah selatan—arah yang akan membawa asap menjauh dari pemukiman penduduk.
Bambu kering dan minyak kelapa disembunyikan dalam karung padi. Sutan Darek dan dua pemuda bertugas mengalihkan perhatian penjaga dengan melempar batu ke sisi barat tembok. Saat dua serdadu keluar mengejar bayangan, Mahara dan tiga lainnya masuk lewat celah pagar belakang.
Dengan gerakan cepat, mereka menyiramkan minyak dan menyisipkan potongan bambu berisi belerang di bawah tumpukan karung. Api dinyalakan dengan lentera kecil, lalu mereka mundur tanpa suara.
Dalam sepuluh menit, gudang meledak dengan bunyi menggelegar. Api membumbung tinggi, membakar cadangan makanan, pakaian seragam, dan amunisi ringan. Orang-orang keluar dari rumah, panik dan bingung. Tapi tak satu pun tahu siapa pelakunya.
Dari kejauhan, Mahara dan Sutan Darek mengamati cahaya merah yang menjilat langit.
“Kita membakar bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa merasa aman di tanah kita,” bisik Mahara.
Keesokan harinya, markas Belanda geger. Letnan Kolonel Van Vliet memerintahkan penggeledahan besar-besaran. Puluhan orang ditangkap tanpa alasan jelas. Bahkan kepala pasar dituduh sebagai simpatisan pemberontak.
Namun di tengah kekacauan itu, satu nama muncul kembali: Rasuan.
Ia muncul di pos penjagaan Belanda dengan wajah cemas. “Saya tahu siapa yang membakar gudang,” katanya. “Dan saya tahu di mana mereka akan menyerang berikutnya.”
Mahara, yang sudah mengantisipasi pengkhianatan ini, telah menyiapkan jebakan.
Rasuan memberi informasi palsu—tanpa ia sadari bahwa informasi itu berasal dari dokumen yang sengaja disebar oleh Rimbo Hitam. Dalam selembar peta, Mahara menandai sebuah lokasi palsu di hutan Talago Gunuo, lengkap dengan nama-nama “anggota pemberontak” yang semuanya fiktif.
Pasukan Belanda langsung bergerak ke sana. Mereka membakar pondok-pondok kosong, menebang pohon, dan menembaki bayangan. Tapi tak ada satu pun yang mereka temukan.
Yang mereka tidak tahu, pada saat bersamaan, Mahara dan pasukannya menyelinap ke gudang senjata di pinggiran timur kota—mengambil belasan senapan tua dan dua peti peluru.
“Ini bukan lagi perang antara kekuatan,” kata Mahara kepada orang-orangnya malam itu. “Ini perang akal. Dan selama kita mengenal tanah ini lebih baik dari mereka, kita belum kalah.”
Datuk Mudo mengangguk. “Tapi Rasuan tidak bisa dibiarkan.”
Mahara memandang api unggun yang bergetar lembut.
“Bukan aku yang akan menjatuhkannya. Biar rakyat yang menentukan. Biar pengkhianatan dibalas oleh kehormatan yang telah ia injak.”
Seminggu kemudian, di pasar Koto Baru, Rasuan ditemukan tewas di selokan, tubuhnya dibungkus tikar dan selembar daun lontar bertuliskan:
“Bagi yang menjual darah saudara, tanah ini menuntut.”
Orang-orang berkumpul melihat jenazahnya. Tak ada satu pun yang berani mengangkat atau menguburkannya. Dalam adat Minangkabau, mati dalam pengkhianatan adalah mati tanpa tanah.
Gerakan Rimbo Hitam makin tumbuh. Kini mereka tak hanya di Lembah Agam, tapi juga mulai muncul di Batusangkar dan sepanjang Sungai Kampar. Nama Mahara mulai disebut dalam surat-surat rahasia dan cerita dari mulut ke mulut.
Namun Mahara tahu, perang sesungguhnya belum datang.
“Ini baru permulaan,” katanya kepada Sutan Darek di sebuah malam yang tenang. “Mereka belum mengirim pasukan sesungguhnya. Dan ketika mereka datang, kita harus sudah siap. Dengan lebih dari sekadar bambu dan panah.”
Sutan Darek menatap Mahara. “Kita akan terus bertarung?”
Mahara mengangguk. “Sampai tanah ini bebas dari sepatu asing. Sampai anak-anak kita tak lagi harus belajar dari bayang-bayang.”
Dan di balik derak pohon bambu malam itu, tanah Minangkabau kembali menyimpan sebuah rahasia: bahwa perang terbesar kadang dimenangkan bukan dengan kekuatan, tapi dengan pikiran dan keberanian untuk melawan tanpa perlu terlihat.*
Bab 6: Peluru dan Pusaka
Langit Minangkabau berubah kelabu sejak kabar itu datang. Belanda mengirimkan satu batalion penuh dari Bukittinggi. Mereka menyebut operasi ini “Pembersihan Tanah Liar.” Tapi bagi Mahara dan pasukan Rimbo Hitam, ini bukan sekadar invasi—ini ujian terakhir, di mana peluru dan pusaka akan bicara.
Di lereng Gunung Sago, Mahara berdiri di depan ratusan pasukan rakyat. Lelaki tua, petani muda, pemuda bekas murid surau, semua berdiri tegak. Tak satu pun dari mereka tentara. Tapi semua punya nyawa untuk ditawarkan.
“Besok mereka datang,” kata Mahara, suaranya berat tapi mantap. “Dan kalian harus tahu… ini mungkin pertempuran terakhir kita di sini.”
Desah pelan terdengar dari barisan. Mahara mengangkat tangannya. “Tapi jika kita harus jatuh, biarlah kita jatuh berdiri. Biarlah mereka ingat bahwa di tanah ini, harga diri lebih mahal dari nyawa.”
Ia menoleh ke Datuk Mudo dan Sutan Darek.
“Siapkan pusaka itu.”
Malam sebelum penyerangan, Mahara menghadap pusaka peninggalan leluhurnya: sebilah keris berukir emas yang dipercaya berasal dari zaman kerajaan Pagaruyung. Tak ada sihir, tak ada kekuatan gaib. Tapi dalam logam tua itu terukir ratusan tahun sejarah, dan Mahara tahu, pusaka itu harus kembali bicara.
“Keris ini bukan untuk membunuh,” katanya kepada Sutan Darek, “tapi untuk mengingatkan: bahwa kita bukan pemberontak. Kita adalah pewaris tanah ini.”
Pagi tanggal 17 April, pasukan Belanda menyerbu dari tiga sisi. Mereka menggunakan meriam ringan, kavaleri, dan pemandu lokal yang dibayar. Desa-desa dibakar untuk memancing Rimbo Hitam keluar dari persembunyian.
Tapi Mahara tidak membalas.
Ia memilih lokasi: lembah kecil antara dua bukit yang dinamai Watas Tigo Batu. Di sanalah jebakan disiapkan—lubang jeblos, ranjau bambu, panah tersembunyi. Tapi senjata utama mereka bukanlah jebakan, melainkan ilusi.
Mahara telah menyusun ratusan batang bambu kering di jalur sempit, digantung dan disangga tali. Ketika pasukan Belanda masuk, tali ditarik—bambu jatuh berderak, menciptakan suara seperti ribuan peluru. Pasukan Belanda panik, melepaskan tembakan membabi buta ke semak.
Lalu panah dan tombak menghujani dari atas.
Pertempuran berlangsung selama lima jam. Mahara, dengan keris di pinggang dan senapan tua di tangan, memimpin langsung. Ia menembak tepat, tapi lebih banyak memberi perintah: “Tahan! Jangan kejar! Pancing mereka ke sisi barat!”
Pasukan kolonial kehilangan arah. Mereka bukan lagi menyerbu, tapi bertahan. Tapi ketika meriam mulai menyalak, tanah bergetar, dan dua barisan Rimbo Hitam di sisi kanan rubuh.
Mahara berlari, tapi terlambat. Datuk Mudo tertembak di dada. Ia tersungkur di bawah pohon beringin.
“Mahara…” bisiknya, “Kau harus tetap hidup… Bukan untuk menang, tapi untuk mengisahkan… agar generasi tahu bahwa kita pernah menolak tunduk…”
Di tengah kekacauan, Mahara mengambil keputusan besar.
“Lepaskan sinyal mundur!” teriaknya.
Bendera merah dilepas di puncak bukit. Semua pasukan segera berpencar—bukan lari, tapi menyusup ke hutan dalam formasi terpisah. Bukan kekalahan, tapi taktik gerilya. Biarkan Belanda mengira mereka menang. Biarkan mereka puas di atas tanah hangus yang tak memberi hasil.
Sutan Darek menarik Mahara dari garis depan. Tapi Mahara berhenti sejenak, menancapkan keris pusaka ke tanah.
“Tanah ini belum selesai,” katanya. “Aku akan kembali.”
Tiga hari setelah pertempuran, Belanda mendirikan tenda kemenangan di Watas Tigo Batu. Mereka mengibarkan bendera, memotret medan, dan menuliskan laporan: “Pemberontak dikalahkan.”
Tapi malam harinya, salah satu tenda meledak. Sebuah ledakan kecil, berasal dari potongan bambu yang diisi belerang—tak mematikan, tapi cukup untuk menimbulkan kepanikan.
Dan di tiang bendera, seseorang menggantungkan sehelai kain bertuliskan:
“Pusaka boleh jatuh, tapi semangat tetap hidup.”
Mahara dan sebagian pasukannya selamat. Mereka berpencar ke hutan Taram, menyamar sebagai petani, pemburu, bahkan pengemis. Tapi benih yang mereka tanam tumbuh: di tiap nagari, anak-anak muda mulai meniru gerakan mereka.
Kini, Rimbo Hitam bukan lagi satu kelompok. Ia menjadi ide—bergerak diam-diam, menyatu dalam masyarakat, menunggu waktu yang tepat.
Mahara menyimpan keris itu dalam balutan kain tua, lalu menguburnya di bawah pohon warisan, di atas bukit kecil yang menghadap ke arah Gunung Sago.
“Suatu hari,” katanya kepada Sutan Darek, “akan ada yang menggali ini kembali. Bukan untuk perang, tapi untuk ingat.”
Sutan Darek menatapnya.
“Kita kalah?”
Mahara menggeleng. “Hari ini mungkin. Tapi selama pusaka itu tidak dibakar, dan sejarah tidak dilupakan, kita belum kalah.”
Dan di bawah langit Minangkabau yang mulai cerah, seorang pemuda yang pernah memimpin perang diam-diam menjadi legenda.*
Bab 7: Pusaka yang Bangkit
Tahun 1950. Lima tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan satu tahun sejak Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik. Tanah Minangkabau tak lagi dipenuhi derap sepatu serdadu asing, tetapi bekas lukanya masih membekas dalam tiap jengkal tanah dan cerita.
Di sebuah surau kecil di kaki Gunung Sago, seorang pemuda bernama Rafli Mahara sedang membersihkan halaman surau tua yang dibangun ulang setelah perang usai. Pemuda ini berusia dua puluh lima tahun, anak dari generasi merdeka, namun mewarisi rasa lapar akan sejarah yang tak diajarkan.
Di rumah neneknya, ada satu cerita yang selalu diceritakan ulang: tentang Mahara, pejuang hutan yang hilang tanpa jejak setelah Pertempuran Watas Tigo Batu. Tentang Rimbo Hitam yang berubah jadi bayang-bayang perjuangan. Dan tentang sebuah pusaka—keris berukir emas—yang tak pernah ditemukan.
“Kalau kau laki-laki, Rafli, suatu hari kau akan mencarinya,” kata sang nenek suatu malam. “Karena kau bukan hanya pewaris nama. Kau pewaris ingatan.”
Hari itu, Rafli menelusuri lereng kecil di balik surau, mengikuti aliran air kecil menuju hutan yang dulu dipercaya sebagai tempat Mahara bersembunyi. Ia membawa cangkul, bukan senjata, dan kompas tua warisan ayahnya. Di tangannya tergenggam peta lusuh yang digambarkan dari cerita lisan neneknya.
Setelah tiga jam berjalan, ia menemukan pohon tua dengan akar melingkar dan batu berlumut yang menyerupai dudukan. Jantungnya berdebar ketika ia mulai menggali.
Satu jam, dua jam. Lalu… klek—cangkulnya membentur sesuatu yang bukan tanah.
Dengan hati-hati, ia menyapu tanah. Sebuah peti kayu kecil, berukir motif Minang, muncul dari balik bumi. Ia mengangkatnya dengan gemetar, membuka dengan napas tertahan.
Di dalamnya, tergeletak sebilah keris emas dengan ukiran halus. Di gagangnya, terukir nama:
Mahara.
Dan selembar surat tua, ditulis dengan tangan, mulai pudar oleh waktu.
“Untuk siapa pun yang menemukan ini, ketahuilah bahwa aku tidak mati. Aku hidup dalam tiap perlawanan, dalam tiap jiwa yang menolak tunduk pada penjajahan. Aku tidak meminta dikenang, hanya dipahami. Bahwa perjuangan bukan untuk dibanggakan, tapi dilanjutkan.”
Air mata Rafli mengalir. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan: seolah suara leluhur memeluknya, membangkitkan rasa yang lebih dalam dari sekadar kebanggaan. Ini bukan hanya warisan darah—ini warisan harga diri.
Kembali ke kampung, Rafli membawa keris itu ke Balai Nagari. Para tetua terdiam ketika melihatnya. Seorang datuk tua berkata dengan suara bergetar, “Ini keris Mahara. Pusaka yang hilang. Kau menemukan sejarah kita.”
Berita itu menyebar cepat. Wartawan, sejarawan, bahkan pemerintah lokal datang. Mereka ingin menulis ulang sejarah lokal yang selama ini hanya jadi bisik-bisik.
Rafli menolak menjual pusaka itu. Sebaliknya, ia membangun Museum Pusaka Perjuangan, sebuah bangunan kecil di kaki bukit yang menyimpan keris Mahara, peta Rimbo Hitam, surat-surat rahasia, dan benda-benda peninggalan rakyat yang ikut bertempur.
Setiap pengunjung membaca kisah itu akan tahu: bahwa sejarah bukan hanya milik jenderal dan istana, tapi juga milik petani bersenjatakan bambu, guru surau, dan anak-anak yang membawa pesan lewat hutan.
Pada peringatan Hari Kemerdekaan tahun itu, Rafli diminta naik ke panggung di depan masyarakat nagari. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana, dengan keris di pinggang—bukan sebagai senjata, tapi sebagai simbol.
Ia berbicara pelan, namun tegas.
“Dulu, di hutan ini, seorang lelaki memilih untuk tidak menyerah. Namanya Mahara. Ia tidak punya medali, tidak punya pangkat. Tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih besar: kehormatan. Tanpa Mahara dan orang-orang seperti dia, kita mungkin tidak berdiri di sini sebagai bangsa.”
Ia mengangkat keris ke udara.
“Ini bukan pusaka perang. Ini pusaka ingatan.”
Malamnya, Rafli duduk sendiri di depan museum. Di belakangnya, lampu-lampu masih menyala. Anak-anak berlarian, orang-orang berbincang dengan gembira. Tapi dalam benaknya, ia melihat sosok Mahara—berdiri di hutan, dikelilingi kabut dan suara bambu.
Lalu, suara neneknya terngiang kembali:
“Sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu seseorang untuk membangunkannya.”
Dan malam itu, Rafli tahu. perjuangan tidak selalu di medan perang. Kadang, perjuangan adalah menjaga agar cerita tidak dilupakan. Agar anak cucu tahu bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit, melainkan tumbuh dari tanah, dari darah, dan dari pilihan untuk melawan.
Epilog
Beberapa tahun kemudian, nama Mahara resmi diakui sebagai pejuang lokal dalam dokumen sejarah daerah. Sekolah-sekolah di Minangkabau mulai mengenalkan kisah Rimbo Hitam sebagai bagian dari pelajaran. Dan di museum kecil di bawah kaki Gunung Sago, setiap tahun, pada tanggal 17 April, warga berkumpul untuk mengenang Pertempuran Watas Tigo Batu.
Tak ada seremoni besar. Hanya pembacaan puisi, cerita dari para tetua, dan anak-anak yang diberi kesempatan menyentuh replika keris Mahara—agar sejarah bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dirasakan.
Dan keris itu, pusaka yang dulu tertanam dalam tanah, kini berdiri dalam kaca, disinari cahaya pagi, mengingatkan semua orang
Bahwa dalam diam, leluhur kita pernah berseru:
“Kami bukan budak. Kami anak tanah ini. Dan kami memilih melawan.”***
_______________THE END_______________