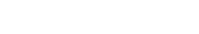Bab 1: Api dalam Senyap
Langit sore di kampung Ngraman dibalut warna tembaga. Angin berhembus pelan, menyusuri pematang sawah yang mulai mengering. Di bawah pohon beringin besar dekat balai desa, seorang pemuda berusia dua puluh tahun duduk bersila, matanya menatap jauh ke arah barat. Itulah Darma, putra dari keluarga priyayi yang memilih jalan berbeda dari ayahnya yang setia kepada pemerintah kolonial.
Darma tumbuh dengan kisah-kisah perjuangan. Dari kakeknya, ia mendengar tentang pemberontakan Diponegoro. Dari ibunya, tentang kaum tani yang dirampas tanahnya. Tapi dari ayahnya, ia hanya mendengar nasihat untuk “tidak ikut campur urusan orang besar.” Bagi Darma, diam bukan pilihan. Ketika tanah sendiri diinjak-injak, dan rakyat hanya dianggap budak di negeri sendiri, maka saatnya angkat suara, meski dengan bisikan.
Di tangannya, Darma menggenggam beberapa lembar pamflet lusuh yang disalin tangan sendiri semalaman. Isinya sederhana, tapi tajam:
> “Bangkitlah, wahai rakyat! Negeri ini bukan milik mereka yang datang dari laut, tapi milik kita yang lahir dari tanahnya!”
Pamflet-pamflet itu akan diselipkan di antara celah pintu toko-toko kecil, dilempar ke pekarangan, atau diselundupkan ke pasar. Semua dilakukan dengan hati-hati. Penjaga Belanda atau polisi pribumi bisa muncul dari mana saja. Dan satu tuduhan makar, cukup untuk membuat seseorang menghilang selamanya.
Sore itu, Darma tak sendiri. Dari balik semak, muncul Ratna, gadis yang wajahnya selalu menyimpan ketenangan, tapi matanya menyala seperti bara. Ia mengenakan kebaya biru sederhana, membawa bungkusan kecil berisi buku-buku dan pamflet lainnya.
“Kau sudah salin semuanya?” tanya Ratna, duduk di samping Darma.
“Ya, semalaman aku menyalin lima belas lembar. Tanganku pegal,” jawab Darma seraya tersenyum.
Ratna tertawa pelan. “Kau belum tahu rasanya menulis pelajaran sejarah tanpa menyebut Belanda sebagai penyelamat.”
Mereka berbagi senyap. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Di tengah keterbatasan, di tengah ketakutan, mereka membangun harapan.
“Mengapa kau masih mengajar?” tanya Darma, memandangnya.
“Aku ingin anak-anak tahu bahwa mereka bukan budak. Mereka harus tahu siapa mereka. Dan kalau mereka tumbuh dengan kesadaran itu, satu generasi lagi cukup untuk mengguncang penjajah dari akarnya.”
Darma mengangguk. Di desa seperti Ngraman, banyak yang sudah menyerah. Ada yang memilih jadi informan demi uang, ada yang pura-pura buta. Tapi di antara semua itu, masih ada yang berani menyalakan nyala kecil.
**
Malam menjelang. Darma kembali ke rumahnya dengan langkah hati-hati. Di ruang tamu, ayahnya sedang duduk membaca koran berbahasa Belanda. Lampu minyak di sudut ruangan menyorot bayangan wajah sang ayah yang tegas dan penuh aturan.
“Dari mana saja?” tanya ayahnya, tanpa menoleh.
“Dari balai desa, mengantar laporan panen.”
“Berhati-hatilah, Darma. Belakangan ini banyak orang ditangkap karena menyebar tulisan-tulisan tak jelas.”
Darma diam. Ia tahu arah pembicaraan itu. Ayahnya dulunya menjabat kepala distrik—tunduk pada pemerintahan kolonial, dihormati karena kedekatannya dengan Belanda. Tapi Darma tahu, kehormatan itu dibeli dengan diam.
“Tak semua tulisan tak jelas, Ayah. Kadang yang tak jelas justru yang dibungkam,” jawab Darma, pelan namun penuh makna.
Ayahnya menatap tajam. “Kau tak akan mengerti dunia ini, Nak. Bertahan hidup lebih penting daripada berteriak dalam gelap.”
Darma hanya menunduk. Tapi di dalam hatinya, ada gelora yang tak bisa diredam.
Keesokan harinya, Darma dan Ratna memulai tugas mereka. Di pagi buta, sebelum pasar ramai, mereka menyebar pamflet. Darma menyelipkan satu di balik rak sayur milik Bu Rini, lalu satu lagi di sela dinding warung Pak Wiryo. Ratna diam-diam menaruhnya di tumpukan daun pisang.
Tiba-tiba, terdengar suara teriakan. Seorang pria berpakaian preman berlari membawa selembar pamflet.
“Ada penyebar hasutan! Tangkap dia!”
Darma dan Ratna berpandangan, lalu segera berpisah arah. Darma berlari melewati gang sempit, menyusup di antara pohon pisang. Ia hampir tertangkap, tapi beruntung, seorang petani tua menariknya masuk ke dalam gudang kecil di belakang rumahnya.
“Diam di sini dulu,” bisik si petani. “Aku tahu siapa kau. Aku percaya pada kata-kata itu. Tapi sekarang, diamlah.”
Darma hanya mengangguk. Jantungnya berdetak kencang, tapi ada rasa haru. Bahkan di antara bayang ketakutan, masih ada yang percaya. Masih ada yang menyimpan api itu.
Malam harinya, mereka berkumpul di rumah Ratna bersama beberapa pemuda desa. Mereka berdiskusi pelan, dalam cahaya redup. Bahasannya bukan sekadar pamflet, tapi langkah selanjutnya: membuat jaringan antar-desa, menyusun sandi, dan menggali sejarah lokal yang bisa membakar semangat.
“Semakin banyak yang tahu sejarahnya sendiri, semakin sulit mereka untuk dijajah,” kata Ratna.
Darma menambahkan, “Kita harus mulai dari dalam. Dari cerita-cerita, dari lagu rakyat, dari doa ibu-ibu. Revolusi tak selalu dengan senjata.”
Malam itu, mereka bersumpah. Dalam ruang sempit dan cahaya lampu minyak, mereka berikrar bukan hanya untuk melawan penjajahan, tapi juga untuk menjaga martabat sebagai manusia merdeka.
Di luar, angin malam membawa bisikan beringin tua, seolah ikut menyaksikan kebangkitan yang baru dimulai.*
Bab 2: Bayang di Balik Penjajahan
1942. Langit Ngraman tak lagi sama. Bendera merah-putih-biru telah diturunkan, diganti oleh matahari terbit dari timur—bendera Jepang yang berkibar tinggi di balai kota. Belanda tumbang, dan tentara Dai Nippon datang dengan janji pembebasan. Namun, rakyat segera menyadari, penjajah hanya berganti rupa.
Darma berdiri di halaman sekolah yang kini dijadikan markas militer Jepang. Di samping gerbang, papan bertuliskan “Gakko Heishadan” — pusat pelatihan pemuda dan milisi lokal. Ia melihat anak-anak muda digiring, berbaris rapi di bawah teriakan seorang tentara Jepang. Senyum Darma menghilang.
“Dulu kita dipaksa tunduk pada Belanda, sekarang dipaksa hormat pada Jepang,” gumamnya.
Di sampingnya, Ratna memeluk buku tulis yang kini berisi pelajaran baru: bahasa Jepang, pujian untuk Kaisar, dan sejarah versi penjajah timur. Ia yang dulu mengajar sejarah bangsa dengan semangat, kini harus menyampaikan kebohongan dengan hati yang perih.
“Aku tidak sanggup lagi,” ucap Ratna lirih. “Anak-anak itu mengucapkan ‘Tenno Heika Banzai’ sambil menunduk, seolah kaisar Jepang dewa mereka. Padahal kita punya kisah sendiri yang jauh lebih agung.”
Darma menggenggam tangannya. “Kita akan terus mengajarkan yang benar. Tapi lebih hati-hati. Jepang lebih kejam dari Belanda. Mereka tidak bicara hukum—mereka bicara darah.”
Malam itu, di sebuah rumah panggung tua di pinggiran desa, sekelompok pemuda berkumpul diam-diam. Wajah-wajah muda penuh semangat tapi juga takut. Mereka menyebut diri “Tunas Merdeka”, sebuah organisasi bawah tanah yang terus bertahan meski rezim berganti.
“Teman-teman, kita sedang diawasi,” kata Darma sambil menatap lingkaran pertemuan. “Tentara Jepang telah menangkap beberapa orang di desa tetangga hanya karena menyembunyikan radio.”
“Radio bukan senjata!” sahut Jaya, pemuda yang baru saja kehilangan kakaknya karena dituduh menyebarkan berita dari luar.
“Bagi Jepang, informasi lebih berbahaya dari peluru,” balas Ratna.
Mereka tahu, berita dari luar negeri—tentang kekalahan Jepang di Pasifik, tentang Amerika yang mulai menyerang balik—adalah cahaya harapan. Tapi untuk mendengarnya saja, nyawa jadi taruhannya.
Darma menarik napas dalam. “Kita harus sembunyikan radio itu di tempat yang bahkan hewan pun enggan masuk.”
“Di gua tua di balik bukit?” tanya salah satu pemuda.
Darma mengangguk. “Mulai malam ini, jaga secara bergilir. Kalau Jepang tahu, kita semua tamat.”
Hari-hari berlalu dalam ketegangan. Jepang memaksa rakyat bekerja rodi—membangun jalan, menggali parit, mengangkut logistik militer. Darma pernah ditangkap karena terlambat hadir di pelatihan milisi. Ia dihukum berdiri di bawah terik matahari selama berjam-jam, lalu dicambuk karena menatap mata tentara terlalu lama.
Namun, luka di tubuh tak sebanding dengan luka di hati ketika ia melihat anak-anak kecil kelaparan. Lumbung padi dirampas, ladang dikuasai militer, dan rakyat hanya diberi nasi jagung atau singkong basi.
Ratna sendiri mulai mengajar kembali—tapi diam-diam. Ia berpura-pura mengajarkan bahasa Jepang, padahal di sela-sela pelajaran, ia menyisipkan sajak dan cerita kepahlawanan.
Suatu malam, ia membacakan cerita tentang Gadjah Mada di hadapan murid-muridnya.
“Aku bersumpah tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu!”
Anak-anak itu terpaku. Seorang dari mereka bertanya, “Apa maksudnya, Guru?”
Ratna menatap mata mereka satu per satu. “Itu berarti kita harus sabar dan kuat menahan segala hal, sampai negeri ini bebas dan bersatu kembali.”
Anak-anak mengangguk, tak semuanya mengerti, tapi ada nyala kecil yang mulai tumbuh.
Pada bulan keempat pendudukan, terjadi hal yang mengejutkan: Mas Wirya kembali ke Ngraman. Lelaki itu dulu dikenal sebagai tokoh pergerakan, sempat hilang sejak masa akhir pemerintahan Belanda. Kini ia datang dalam seragam lengkap—tapi bukan seragam Belanda ataupun Jepang. Ia mengenakan pakaian sipil, tapi dibarengi pengawalan dari tentara Jepang.
“Mas Wirya dipercaya sebagai penasehat lokal bagi pemerintah militer,” kata Kepala Desa saat mengumumkan kedatangannya.
Darma dan Ratna saling pandang. Ada keganjilan yang sulit diabaikan. Bagaimana bisa orang yang dulu anti-penjajah kini begitu dekat dengan mereka?
Dalam pertemuan di balai desa, Mas Wirya berbicara lantang.
“Kita tidak bisa terus melawan. Sekarang saatnya bekerja sama. Jepang datang untuk membebaskan kita dari Barat. Mari kita bantu agar bangsa ini menjadi bagian dari Asia Raya yang kuat!”
Sorak setengah paksa terdengar. Tapi tidak semua percaya.
“Dia pengkhianat,” bisik Ratna pada Darma.
“Belum tentu,” jawab Darma perlahan. “Atau… mungkin benar, tapi kita perlu bukti. Jangan bergerak gegabah.”
Beberapa minggu kemudian, Darma mendapatkan kesempatan langka. Salah satu pemuda dari kelompok Tunas Merdeka, Anton, bekerja di dapur markas Jepang. Ia mendengar kabar bahwa Mas Wirya sering mengadakan pertemuan rahasia dengan perwira Jepang, bukan untuk membela rakyat, tapi untuk memastikan para pemberontak dibasmi sebelum bergerak.
Darma marah. Tapi ia menahan diri.
“Kita butuh bukti tertulis. Kalau kita bisa menyusup dan mencuri catatan itu—entah laporan atau daftar nama—maka semua akan tahu siapa dia sebenarnya,” kata Darma saat pertemuan rahasia.
Namun, menyusup ke markas Jepang bukan tugas mudah. Ada penjaga, anjing, dan hukuman mati.
“Aku yang akan masuk,” ucap Darma akhirnya.
“Tidak!” seru Ratna. “Kau bisa terbunuh!”
“Tapi kalau kita terus menunggu, mereka yang akan membunuh kita satu per satu.”
Malam itu, Darma bersiap. Ia mengenakan pakaian petani, membawa keranjang kosong. Lewat celah pagar belakang markas, ia menyusup saat para penjaga sedang sibuk dengan inspeksi mendadak dari pusat.
Ia masuk ke gudang tua yang dijadikan tempat arsip. Jantungnya berdetak cepat saat ia menemukan berkas berisi daftar tahanan dan laporan dari Mas Wirya kepada kepala kamp militer. Isinya jelas: nama-nama pemuda yang diawasi, termasuk Darma dan Ratna.
Langkah kaki terdengar di luar. Darma menggenggam berkas itu dan melompat keluar jendela kecil, mendarat di lumpur, lalu berlari menyusuri pematang.
Peluru meletus di belakangnya. Tapi malam menyelamatkannya.
Di rumah Ratna, Darma membuka berkas itu di hadapan semua anggota Tunas Merdeka. Mata mereka tak berkedip saat membaca nama-nama teman mereka yang sudah menghilang—ternyata diserahkan oleh Mas Wirya sendiri.
“Kita punya bukti,” ucap Darma, suara gemetar.
“Tapi apa kita punya keberanian untuk menghadapinya?”
tanya Jaya pelan.
Ratna menatap langit malam, bintang-bintang bertebaran di atas kepala mereka.*
Bab 3: Sumpah Darah di Rawa Gelap
Rawa Gelap. Tempat yang disebut-sebut angker oleh warga desa. Di siang hari, rawa ini sunyi dan tertutup kabut tipis. Tapi di malam hari, ia seperti menghisap cahaya, menyembunyikan bayang-bayang dan rahasia. Di sinilah Darma dan rekan-rekannya dari Tunas Merdeka berkumpul malam itu, jauh dari mata-mata Jepang, jauh dari pengkhianatan Mas Wirya.
Darma berdiri di tengah lingkaran. Di tangannya masih tergenggam erat berkas rahasia yang berhasil ia curi dari markas militer Jepang seminggu lalu. Laporan itu menjadi bukti pengkhianatan Mas Wirya, tokoh yang dulu mereka percaya, tapi kini terbukti menyerahkan nama-nama pejuang kepada penjajah demi kekuasaan.
“Teman-teman,” ucap Darma lantang, “sekarang kita tak bisa hanya bersembunyi. Kita tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Kita harus bersumpah malam ini. Sumpah darah, bahwa kita akan terus berjuang, meski harus kehilangan nyawa.”
Satu per satu, mereka mengangguk. Wajah-wajah muda itu diliputi cahaya remang dari obor bambu yang berkedip ditiup angin rawa. Ratna maju, menggenggam tangan Darma.
“Kita bukan pemberontak,” katanya, “kita pewaris tanah ini. Dan siapa pun yang menjual negeri ini, meski darahnya sama dengan kita, tetaplah pengkhianat.”
Jaya, Anton, dan delapan anggota lainnya melingkari sebuah batu datar. Darma mengeluarkan pisau kecil, menggoreskan luka ringan di telapak tangan. Ia meneteskannya di atas batu, diikuti yang lain. Campuran darah itu jatuh di permukaan lembab, meresap ke tanah yang sama tempat nenek moyang mereka pernah tumpah darah demi tanah ini.
“Demi tanah ini, demi langit yang menaunginya, dan demi masa depan anak cucu kita,” kata Darma. “Kita bersumpah tak akan berhenti sebelum tanah ini bebas!”
“MERDEKA!” seru mereka serempak, meski pelan, seolah takut suara mereka menembus kabut dan membawa maut.
**
Setelah pertemuan itu, Tunas Merdeka bergerak cepat. Dengan dokumen yang mereka miliki, mereka memulai dua hal: menyebarkan selebaran berisi bukti pengkhianatan Mas Wirya, dan menyusun serangan kecil terhadap gudang logistik Jepang di pinggiran hutan Ngraman.
Namun, Jepang juga tidak tinggal diam.
Selama dua minggu, penjagaan diperketat. Desa-desa digeledah. Warga ditangkap tanpa alasan. Jepang tahu ada pergerakan di balik kabut rawa. Mereka tidak tahu siapa dalangnya, tapi mereka tahu: api sedang menyala.
Suatu malam, Darma, Jaya, dan Anton menyusup ke gudang logistik. Mereka bergerak di bawah bayangan pepohonan, menghindari anjing penjaga dan patroli. Dengan bahan bakar dan kain, mereka membakar persediaan makanan militer. Kobaran api menyala tinggi, dan suara letusan terdengar saat beberapa amunisi ikut terbakar.
Misi berhasil. Tapi harga yang harus dibayar mahal.
Anton tertangkap saat melarikan diri. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan tergantung di alun-alun desa. Sebuah papan kayu tergantung di lehernya bertuliskan: “Contoh bagi pengkhianat.”
Ratna menangis dalam diam. Darma menggenggam pundaknya. “Anton tak mati sia-sia. Setiap tetes darahnya menambah kekuatan kita.”
Sementara itu, Mas Wirya tak tinggal diam. Ia merasa posisinya terancam oleh pamflet-pamflet yang menyebar di seluruh desa. Namanya tercemar. Untuk membungkam pemberontakan, ia meminta izin kepada komandan Jepang untuk menangkap Darma secara diam-diam.
“Dia hanya anak muda. Tapi pengaruhnya menyebar seperti api,” kata Mas Wirya dalam bahasa Jepang terbata. “Kalau tidak dihentikan sekarang, kita akan kehilangan kendali.”
Perintah penangkapan keluar. Darma menjadi buruan resmi. Tapi ia lebih dulu mengetahui rencana itu dari salah satu informan mereka di markas.
Malam itu, Darma dan Ratna melarikan diri ke pegunungan di utara Ngraman. Dalam pelarian itu, mereka melewati hutan, sungai, dan desa-desa kecil. Di sela-sela pelarian, Ratna sempat bertanya:
“Apakah kau menyesal, Darma?”
“Menyesal?” Darma menoleh padanya. “Kalau aku menyesal, aku tak akan berdiri di sini bersamamu.”
Ratna tersenyum pahit. “Aku takut kehilanganmu. Aku takut bangun suatu hari dan namamu hanya tinggal cerita.”
Darma meraih tangannya. “Kalau suatu hari aku tiada, pastikan kau tetap bercerita. Itulah caranya aku tetap hidup.”
Di hutan perbatasan, Darma dan Ratna menemukan markas kecil milik sisa-sisa tentara PETA (Pembela Tanah Air) yang kecewa dengan Jepang. Di sana, mereka disambut oleh pemuda-pemuda dari berbagai wilayah, semuanya memiliki luka dan kehilangan yang sama.
Darma menyampaikan pidatonya di hadapan mereka:
“Kita semua datang dari arah berbeda, tapi tujuan kita sama. Kita bukan milik Belanda, bukan milik Jepang. Kita milik tanah ini. Dan kalau kita mati hari ini, biarlah mati dalam kehormatan.”
Pasukan kecil itu mulai membangun rencana untuk menyerbu kantor distrik yang dikuasai Jepang di pusat Ngraman. Bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk menunjukkan bahwa rakyat belum tunduk.
Rencana disusun dengan hati-hati. Sandi dikirimkan melalui anak-anak desa, dan sinyal ditandai dengan cahaya obor di puncak bukit.
Namun, menjelang hari penyerbuan, seorang kurir mereka tidak kembali.
Ratna gemetar. “Jangan-jangan rencana kita bocor.”
Darma menatap nyala obor yang berkedip lemah di kejauhan. “Kalau memang bocor, maka kita akan berperang. Tapi lebih baik mati dalam perang daripada hidup dalam pengkhianatan.”
Dan malam pun tiba. Malam ketika sejarah akan ditulis dengan darah.
Darma memimpin pasukan kecilnya menyusuri jalur sempit menuju pusat distrik. Di sisi lain, pasukan Jepang telah bersiap, diberi informasi oleh seseorang dari dalam.
Saat suara peluit pertama berbunyi, tembakan pertama dilepaskan. Perang kecil meletus di tengah gelap malam. Jeritan, letusan, dan dentuman memenuhi udara Ngraman.
Darma melihat Ratna jatuh ke tanah, lututnya berdarah. Ia berlari mendekat, menariknya ke balik tembok.
“Aku tak apa,” Ratna berkata sambil menahan nyeri. “Pergilah. Teruskan.”
Tapi Darma tetap bersamanya. Ia menembakkan senapan bambu ke arah musuh, melindungi Ratna dengan tubuhnya.
Dari kejauhan, sosok Mas Wirya muncul. Ia berdiri di belakang barisan Jepang, memberikan aba-aba, mata dingin menatap Darma.
Darma tahu, malam itu bukan hanya tentang kemerdekaan. Tapi tentang pengkhianatan yang harus ditebus.
Dengan darah.*
Bab 4: Kemerdekaan yang Berdarah
Fajar merekah di atas langit Ngraman, tapi bukan cahaya damai yang terpancar dari langit timur—melainkan kabut tipis yang bercampur dengan asap mesiu dan aroma darah. Pertempuran semalam di kantor distrik telah usai. Namun, bukan kemenangan yang mereka dapat, melainkan luka dan kehilangan.
Darma duduk di tepi bukit, menggenggam tangan Ratna yang terbaring lemah. Luka di kakinya telah dibalut, tapi wajahnya pucat. Nafasnya pelan.
“Maafkan aku,” bisik Darma.
Ratna membuka mata, senyumnya lirih. “Untuk apa kau minta maaf? Kita sudah memilih jalan ini, Darma. Dan aku akan tetap di sisimu, sampai akhir.”
Di bawah mereka, terlihat puing-puing kantor distrik. Sebagian terbakar, sebagian berdiri remuk. Dari pasukan kecil Darma, hanya separuh yang selamat. Beberapa tertangkap, dan yang lainnya… tinggal nama.
Namun, dari reruntuhan itu, lahir sesuatu yang tak bisa dibunuh: keberanian.
**
Di desa, rakyat mulai berani bicara. Selebaran yang ditemukan setelah penyerbuan menyebar cepat, berisi fakta pengkhianatan Mas Wirya dan daftar nama-nama korban yang diserahkan kepada Jepang.
Warga mulai bergumam di warung, di ladang, di dapur: “Darma benar… Wirya bukan pahlawan, dia pengkhianat.”
Mas Wirya tahu posisinya genting. Ia mendesak militer Jepang untuk mengambil tindakan tegas. Tapi Jepang juga dalam posisi goyah. Berita tentang kekalahan Jepang di Filipina, di Iwo Jima, bahkan di Burma mulai masuk lewat radio gelap yang terus disembunyikan rakyat.
“Jika Kaisar kalah, maka kalian semua akan mati seperti tikus,” ancam salah satu perwira Jepang saat rapat terbatas di markas.
Mas Wirya hanya diam. Dalam hatinya, kekuasaan yang dulu terasa kuat kini mulai retak. Ia merasa seperti dinding tua—megah tapi rapuh di dalam.
**
Sementara itu, Darma dan kelompok kecilnya bergerak lebih hati-hati. Mereka menyelinap dari desa ke desa, membangun jaringan baru dengan petani, pemuda, bahkan beberapa guru yang diam-diam mendukung gerakan rakyat.
Ratna, meski belum pulih sepenuhnya, tetap menulis dan mengajar anak-anak. Kali ini bukan hanya sejarah, tapi juga harapan. Ia menyisipkan cerita tentang bangsa-bangsa yang bangkit dari penjajahan, dan bagaimana kemerdekaan adalah hak, bukan hadiah.
“Satu kata yang sederhana,” kata Ratna kepada muridnya. “MERDEKA. Tapi untuk mengucapkannya dengan utuh, kadang kita harus kehilangan banyak.”
Darma memperhatikan dari kejauhan, mata berkaca. Dalam hatinya, ia tahu: Ratna adalah jiwanya. Dan jiwanya terluka bersama tanah ini.
**
Agustus 1945. Dunia berubah.
Sebuah siaran gelap masuk lewat radio tua di gua tempat Darma menyimpan pesan-pesan rahasia. Suara bergetar dari Jakarta:
“Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia…”
Suara Soekarno bergema dalam ruang sempit itu. Para pemuda tak percaya. Beberapa menangis. Darma terdiam.
Ratna menutup mulutnya, bergetar. “Benarkah… kita merdeka?”
Namun, Darma tak menjawab. Matanya tajam menatap horizon.
“Kemerdekaan yang diumumkan di Jakarta belum tentu sampai ke Ngraman. Kita harus merebutnya di sini.”
**
Dan benar. Jepang di Ngraman tidak mau menyerah. Mereka masih bersikeras bahwa berita kemerdekaan adalah propaganda. Mas Wirya memanfaatkan kekacauan ini. Ia berusaha kembali memegang kendali.
Ia mengumpulkan orang-orang desa, memaksa mereka tetap tunduk.
“Jangan percaya pada kabar bohong,” katanya. “Selama tentara Jepang masih di sini, kita tunduk pada mereka. Kalau tidak, kalian akan dihancurkan!”
Namun, rakyat sudah berubah. Tak ada lagi yang tunduk seperti dulu. Mata mereka penuh amarah. Dan keberanian sudah tidak bisa dibungkam.
Malam itu, Darma dan pasukannya menyerbu rumah Mas Wirya. Tapi Mas Wirya sudah pergi, melarikan diri ke arah selatan bersama dua pengawal Jepang yang masih tersisa. Mereka membawa senjata dan sejumlah emas yang dikumpulkan selama menjabat.
Pengejaran pun dimulai.
**
Di tengah hutan selatan Ngraman, pertempuran kecil kembali pecah. Darma dan Jaya memimpin lima pemuda menghadang pelarian. Tembakan bersahut-sahutan. Satu pengawal Jepang tertembak, yang satu lagi melarikan diri.
Mas Wirya tertangkap.
Darah menetes dari pelipisnya, tapi matanya tetap menyala—bukan dengan penyesalan, tapi dengan kebencian.
“Kalian pikir kalian menang? Negara ini akan hancur dalam lima tahun. Kalian tidak tahu bagaimana memimpin, hanya tahu melawan. Kalian akan saling bunuh setelah ini.”
Darma menatapnya, lama. Lalu ia berkata dengan tenang, “Mungkin kau benar. Mungkin kami akan salah langkah. Tapi setidaknya, kami melangkah untuk tanah kami sendiri.”
Mas Wirya dibawa kembali ke desa. Tapi Darma menolak membunuhnya.
“Kita tak bisa menjadi seperti dia. Biarlah rakyat yang menghakimi.”
Dan rakyat pun bicara. Di alun-alun desa, di bawah bendera merah putih yang baru dikibarkan oleh anak-anak desa, Mas Wirya diadili oleh warga yang dulu dipimpinnya. Tidak dengan peluru, tapi dengan suara.
Putusan rakyat: pengasingan. Mas Wirya dibuang ke pinggir desa, tanah yang dulu ia abaikan.
**
Hari itu, 20 Agustus 1945, Ngraman mengangkat bendera merah putih secara resmi. Darma berdiri di tengah lapangan, menggenggam tali pengerek. Ratna di sampingnya, menopang dengan tongkat kayu.
Anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan, meski tak semua nada tepat, tapi penuh semangat.
Saat bendera sampai di puncak, Darma menatap langit. Di sana, awan bergerak pelan. Bebas.
“Ini baru permulaan,” bisik Ratna.
Darma tersenyum. “Tapi kita akhirnya bisa mengucapkannya tanpa rasa takut.”
“MERDEKA.”
**
Namun, bayangan belum sepenuhnya pergi. Di kejauhan, kabar beredar bahwa Belanda ingin kembali. Bahwa Jepang akan benar-benar angkat kaki, tapi kekosongan itu akan diisi penjajah baru.
Darma tahu, perjuangan belum usai.
Tapi hari itu, mereka mencatat sejarah mereka sendiri. Bukan dari buku, bukan dari siaran radio. Tapi dari darah, air mata, dan sumpah yang pernah mereka ucapkan di Rawa Gelap.
Dan sejarah itu tidak akan pernah padam.*
Bab 5: Kembali ke Medan Api
September 1945. Angin belum sepenuhnya berubah. Meski bendera merah putih berkibar di Ngraman, kabar dari luar datang dengan wajah muram. Belanda, yang menamakan diri mereka “NICA”, mulai mendarat di berbagai wilayah dengan dukungan tentara Sekutu. Mereka datang bukan sebagai pembebas, tapi sebagai penjajah lama yang kembali menagih takhta.
Kekacauan pun melanda. Para pejuang muda yang baru merasakan euforia kemerdekaan kini harus kembali memanggul senjata. Damai yang sempat singgah, ternyata hanya jeda dari badai yang lebih besar.
**
Di desa Ngraman, Darma duduk bersama Jaya dan para pemuda. Ratna berdiri di dekat jendela, mendengarkan dari kejauhan sambil menyalin berita dari siaran radio gelap yang masih mereka simpan.
“Surabaya memanas,” kata Ratna lirih. “Pemuda-pemuda bersenjata menyerang markas NICA. Banyak korban, tapi semangat mereka tak padam.”
Jaya mengepal tangannya. “Kalau mereka bisa, kenapa kita harus diam? Kita harus ke sana, bantu saudara-saudara kita.”
Darma menunduk. Pikirannya kacau. Ia ingin bertempur. Ia ingin berdiri bersama rakyat Surabaya. Tapi ia juga tahu, Ngraman belum sepenuhnya aman.
“Satu langkah salah,” ucapnya, “dan kita bisa kehilangan segalanya.”
Namun, malam itu, Darma membuat keputusan. Ia menunjuk dua orang kepercayaannya untuk menjaga Ngraman. Sementara ia, Jaya, dan enam pemuda lainnya bersiap menuju Surabaya. Ratna menatapnya dengan mata berkaca.
“Kau pasti kembali, kan?” tanyanya lirih.
Darma mengangguk, memeluknya erat. “Aku harus kembali. Karena aku belum selesai menulis kisah kita.”
**
Perjalanan ke Surabaya bukan hal mudah. Mereka melewati hutan, menyelinap lewat jalur rel kereta yang terbengkalai, dan sesekali menumpang truk sayuran yang bersedia membantu. Di sepanjang jalan, mereka melihat sisa-sisa perlawanan: rumah terbakar, mayat tertutup daun, dan rakyat yang mengungsi dengan wajah kehilangan.
Di tengah perjalanan, mereka bertemu rombongan pemuda dari Kediri. Salah satunya adalah Rendra, bekas pelajar sekolah guru, yang kini membawa senjata dan semangat membara.
“Kota ini sedang menyala,” kata Rendra. “Tapi apinya butuh bahan bakar. Kalian datang di waktu yang tepat.”
**
Surabaya, awal Oktober.
Kota ini seperti dapur api. Bangunan setengah hancur, jalanan dipenuhi barikade bambu runcing dan drum kosong. Poster-poster bertuliskan “Sekali Merdeka Tetap Merdeka” menempel di setiap sudut, berdampingan dengan bendera merah putih yang compang-camping tapi tegak.
Darma dan rombongannya langsung bergabung dengan para pejuang lokal yang dipimpin Bung Suro—mantan tentara KNIL yang membelot ke pihak republik. Bung Suro menyambut mereka dengan pelukan.
“Semakin banyak tangan, semakin kuat perlawanan ini,” katanya. “Tapi ingat, bukan semua orang di sini teman.”
Kata-kata itu terbukti tak lama setelahnya. Di antara para pejuang, tersebar kabar bahwa NICA menyusupkan mata-mata dengan penyamaran sebagai pemuda. Darma pun mulai berhati-hati, hanya percaya pada lingkaran kecilnya.
**
Pertempuran pertama mereka terjadi pada malam 21 Oktober. NICA mencoba mengambil alih gudang logistik rakyat di Tanjung Perak. Darma, Jaya, dan Rendra memimpin serangan balik bersama puluhan pemuda lainnya.
Dengan senjata seadanya—senapan tua, bambu runcing, dan molotov rakitan—mereka menyerbu pos NICA. Darma menjeritkan seruan kemerdekaan di tengah hujan peluru. Saat salah satu temannya roboh, ia tetap maju, menghancurkan pos komunikasi musuh.
Pertempuran berlangsung sengit. Tapi kali ini, rakyat menang.
Namun, kemenangan itu dibayar mahal. Dua orang pemuda dari Ngraman tewas, dan Jaya tertembak di bahu. Saat Darma membalut lukanya, Jaya tertawa getir.
“Dulu aku takut mati, Dar,” gumamnya. “Sekarang… aku takut mati tanpa hasil.”
Darma menatap sahabatnya. “Setiap peluru yang kita lawan, itu hasil. Setiap langkah kita, itu sejarah.”
**
Pada awal November, situasi makin panas. Sekutu yang dipimpin Inggris mulai melancarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjata. Bung Suro menolak mentah-mentah.
“Senjata bukan hanya besi, tapi martabat,” katanya. “Jika kami menyerah, maka kami menyerahkan harga diri bangsa.”
Pertempuran besar pun tak terelakkan.
10 November 1945. Darma dan para pemuda dari Ngraman ikut serta dalam Pertempuran Surabaya. Mereka berada di lini kedua, menjaga jalur suplai dan membawa logistik ke garis depan.
Langit Surabaya berwarna kelabu. Pesawat tempur melintas, bom jatuh dari udara. Rumah, masjid, sekolah—semuanya menjadi puing.
Namun, tak satu pun dari mereka mundur.
Darma menyaksikan anak-anak kecil membawa air minum untuk pejuang. Wanita-wanita tua menyobek kain untuk perban. Tua, muda, laki, perempuan—semua bertempur dengan cara masing-masing.
Ketika malam tiba, kota ini berubah menjadi lautan doa dan tangis.
**
Dalam kekacauan itu, Darma mendengar kabar buruk: Bung Suro gugur. Rendra hilang. Dan Jaya sekarat.
Ia menemukan Jaya tergeletak di lorong sempit, darah mengalir dari perutnya. Matanya mulai redup.
“Darma…” bisiknya.
“Jaya! Bertahan! Aku akan—”
“Tak perlu,” potong Jaya, tersenyum lemah. “Aku sudah melihat… kemerdekaan. Itu cukup.”
Darma menggenggam tangannya. Air mata mengalir di pipinya. Ia ingin berteriak, tapi hanya bisa membisikkan doa.
Jaya meninggal di pelukannya.
**
Tiga hari setelah itu, Darma kembali ke Ngraman. Tubuhnya penuh luka, tapi jiwanya lebih parah. Ia datang dengan kabar kematian, dengan wajah yang kehilangan banyak.
Ratna menyambutnya dengan tangis. Ia tahu dari tatapan mata Darma—ada yang tidak kembali.
Darma mengumpulkan warga di alun-alun. Di bawah bendera yang sama, ia bercerita tentang Surabaya, tentang Jaya, tentang mereka yang gugur tapi tidak mati sia-sia.
“Mereka tidak hilang,” katanya. “Mereka hidup dalam napas kita. Dalam tanah yang kita pijak. Dalam anak-anak yang kita ajar.”
Ratna memeluknya, erat. “Kau kembali, Darma. Itu cukup.”
Darma menatap langit sore. Di sana, awan bergerak pelan. Dan di tengah kabut luka dan kehilangan, ia tahu: api perjuangan belum padam.*
Bab 6: Warisan di Tanah Merdeka
Tahun 1950. Lima tahun telah berlalu sejak proklamasi dikumandangkan, sejak darah tumpah di jalanan Surabaya, sejak Darma dan ribuan pemuda lainnya mengangkat senjata melawan kembalinya penjajahan. Kini Indonesia berdiri sebagai negara merdeka—walau belum sepenuhnya utuh, dan luka lama masih membekas dalam dinding sejarahnya.
Desa Ngraman berubah. Jalan tanah yang dulu becek kini sudah berlapis batu. Sekolah rakyat berdiri dengan papan nama: Sekolah Merdeka Ratna-Jaya, didirikan dari sumbangan rakyat dan tenaga para pemuda yang selamat dari pertempuran.
Di ruang kelas itu, anak-anak kecil duduk bersila, belajar membaca, menulis, dan menyebut nama-nama pahlawan lokal—bukan hanya yang dari Jakarta, tapi juga dari tanah mereka sendiri: Darma, Jaya, Ratna, dan bahkan para petani tak dikenal yang diam-diam menjadi penyambung nyawa republik.
**
Darma kini tidak lagi memanggul senjata. Ia mengenakan baju sederhana, bertani di pagi hari, dan mengajar di sore hari. Tapi bekas luka di lengannya masih ada, begitu pula dalam hatinya.
Setiap hari, ia menatap foto-foto sahabatnya yang gugur: Jaya dengan senyum nakalnya, Rendra yang sempat menulis puisi di parit pertahanan, Bung Suro yang dengan tegas menolak ultimatum.
Ratna kini menjadi kepala sekolah. Meski kesehatannya tak sekuat dulu, semangatnya justru semakin berkobar. Ia menulis buku-buku pelajaran sendiri, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak desa.
“Kita tak boleh lupa,” katanya pada Darma suatu malam, di teras rumah mereka. “Kemerdekaan itu bukan akhir, Darma. Itu awal dari perjuangan yang lebih sunyi—mendidik, membangun, dan menjaga agar darah yang sudah tumpah tidak sia-sia.”
Darma mengangguk, memandang ke arah sawah yang terbentang luas. Di sana, anak-anak bermain dengan bendera kecil buatan tangan. Tawa mereka menyembuhkan luka yang pernah membakar desa ini.
**
Namun, tidak semua damai.
Beberapa bekas kolaborator seperti Mas Wirya kembali muncul ke permukaan, mencoba memperbaiki citra. Ia kembali dari pengasingan dengan wajah lebih tua, lebih kurus, tapi tetap dengan mata penuh ambisi.
Ia mendekati pemerintahan lokal yang mulai terbentuk, menawarkan pengalaman dan koneksi. Dan sayangnya, beberapa pejabat muda yang belum mengenal masa lalu, tergoda oleh janjinya.
Suatu hari, Mas Wirya muncul di rapat desa, menawarkan pembangunan jembatan dan program pertanian dengan modal dari luar.
“Kita bisa modern, cepat, dan sejahtera,” katanya. “Tapi kita butuh orang-orang yang paham cara kerja kekuasaan.”
Darma berdiri di tengah forum, matanya tajam. “Kita sudah pernah mempercayakan desa ini pada orang yang ‘paham kekuasaan’, dan kita tahu ke mana arah itu membawa kita.”
Tepuk tangan bergemuruh. Warga tidak lupa. Sejarah mungkin bisa dikelabui, tapi mereka yang hidup di dalamnya tetap jadi penjaga ingatan.
Mas Wirya pun pergi lagi—kali ini tanpa kehormatan, tanpa simpati.
**
Beberapa bulan kemudian, surat undangan dari Jakarta tiba. Nama Darma diusulkan menjadi salah satu penerima Bintang Gerilya, penghargaan bagi mereka yang bertempur untuk kemerdekaan di garis depan.
Namun, Darma menolak.
“Aku bukan pejuang karena ingin tanda jasa,” ucapnya. “Tanda jasa terbaik adalah melihat anak-anak kita hidup dalam tanah yang bebas, belajar dengan damai, dan menyebut kata ‘Indonesia’ tanpa rasa takut.”
Ratna mendukung keputusannya. Tapi diam-diam, ia menulis surat balasan ke kementerian. Dalam surat itu, ia menceritakan bagaimana Darma bukan hanya pejuang senjata, tapi pejuang jiwa—yang mengobati luka rakyat dengan kehadiran, bukan pidato.
Beberapa bulan kemudian, surat kedua datang. Kali ini bukan undangan, tapi ucapan terima kasih. Nama Darma dicatat dalam arsip nasional, sebagai tokoh rakyat yang menolak penghargaan demi kejujuran sejarah.
**
Di akhir tahun, Darma dan Ratna memimpin acara peringatan kemerdekaan desa. Di lapangan, anak-anak berdiri berbaris. Bendera merah putih dinaikkan oleh cucu Pak Lurah, dan lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan dengan penuh semangat.
Darma berdiri di depan podium sederhana. Suaranya tenang tapi tegas.
“Dulu, kita bertarung dengan bambu runcing. Hari ini, kita bertarung melawan kebodohan, keserakahan, dan lupa diri. Jangan pernah lupakan mereka yang telah pergi—karena dari tanah merekalah kita berdiri.”
Di akhir pidatonya, Darma menunduk, menatap tanah. Di tempat yang sama, Jaya dulu pernah menjeritkan “Merdeka!” sambil mengangkat bambu berdarah.
Kini, bambu itu disimpan di ruang kecil di sekolah. Sebagai bukti. Sebagai warisan.
**
Beberapa minggu kemudian, Ratna jatuh sakit. Usianya belum tua, tapi tubuhnya sudah lama lelah. Penyakit paru-paru yang dideritanya sejak perang semakin parah. Ia terbaring di ranjang bambu, di dekat jendela tempat angin lembut masuk dari ladang.
Darma duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya yang dingin.
“Kalau aku pergi duluan,” bisik Ratna, “lanjutkan cerita kita. Jangan biarkan mereka yang lahir nanti melupakan apa yang pernah terjadi.”
“Aku tak akan lupa,” jawab Darma, suaranya gemetar. “Karena kamu adalah bagian dari tanah ini.”
Malam itu, Ratna pergi dalam tidur. Damai. Dan di hari pemakamannya, seluruh desa datang. Tak ada tangisan histeris, hanya doa, dan janji dalam hati setiap orang: Kami akan menjaga tanah ini. Kami akan menjaga nama kalian.
**
Tahun-tahun berlalu. Darma menua. Rambutnya memutih, tubuhnya mulai membungkuk. Tapi ia masih berjalan setiap pagi ke sekolah, menyapa anak-anak, menyiram tanaman di halaman, dan sesekali bercerita tentang masa lalu.
“Dulu, kakek pernah menggenggam senjata,” katanya pada seorang bocah. “Tapi hari ini, senjata terbaikmu adalah pena.”
Suatu pagi, Darma tak datang ke sekolah. Para guru mencarinya, dan menemukannya duduk di bawah pohon waringin, tempat ia dan Ratna dulu sering membaca buku bersama. Matanya terpejam, senyum tipis menghiasi wajahnya.
Ia telah pergi, menyusul Ratna.
Di saku bajunya ditemukan sebuah kertas kecil. Tulisannya sederhana, namun menggema:
> “Kemerdekaan bukan hanya milik mereka yang mengangkat senjata. Tapi juga milik mereka yang menjaga nyala perjuangan agar tak padam di hati generasi berikutnya.
Jangan biarkan kami hanya jadi nama di buku. Ingat kami sebagai tanah yang kalian pijak, udara yang kalian hirup, dan sejarah yang kalian lanjutkan.”
**
Kini, di Ngraman, setiap tanggal 17 Agustus, nama Darma dan Ratna disebut dalam doa dan cerita. Sekolah itu masih berdiri. Anak-anak masih menyanyikan lagu kemerdekaan, dan bendera itu masih berkibar—meski warnanya mulai pudar, tapi maknanya tetap merah dan putih.
Dan dari jauh, dari tanah yang pernah berdarah, lahirlah bangsa yang terus belajar berdiri.***
__________THE END_________